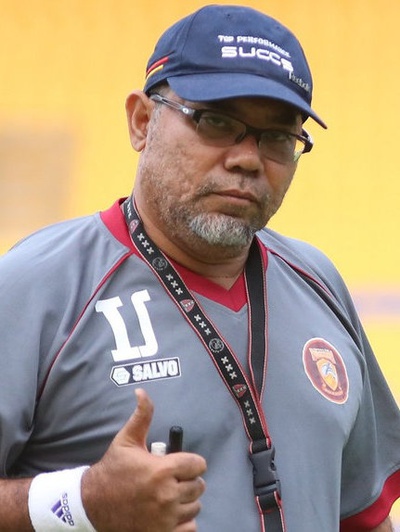Sentimen
Informasi Tambahan
Kab/Kota: Gunung
Kasus: PHK
Tokoh Terkait
Bukan Semata Soal Sritex
 Espos.id
Jenis Media: Kolom
Espos.id
Jenis Media: Kolom

Nasib ribuan karyawan PT Sri Rejeki Isman (Sritex) yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) tiba-tiba jadi materi pembahasan penting pemerintah pusat. Padahal, tumbangnya industri tekstil dalam negeri tidak datang tiba-tiba.
Pemerintah kini sibuk dengan skema-skema menghidupkan kembali korporasi yang berdiri sejak 1966 itu. Berbagai narasi penyelamatan muncul dari pemerintah pusat melalui sejumlah menteri. Salah satunya datang dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi yang mengatakan Sritex akan buka dengan skema baru agar ribuan karyawan bisa kembali bekerja dalam dua pekan.
Ucapan Prasetyo mewakili keinginan Presiden Prabowo Subianto yang bisa jadi punya beban moral menyelamatkan Sritex. Ada pula narasi lain yang menyebut sebuah perusahaan rokok siap menampung karyawan Sritex yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Hiruk pikuk wacana penyelamatan belum jelas kepastiannya. Ini karena penyelamatan Sritex tidak mudah dilakukan apa pun skemanya. Misalnya jika Sritex hendak dijual ke korporasi swasta lain, itu tidak mudah karena perusahaan tersebut terbelit tumpukan utang hingga US$1,6 miliar atau sekitar Rp25,1 triliun.
Skenario lain yang beredar adalah penyelamatan melalui pembelian oleh badan usaha milik negara (BUMN). Belakangan muncul spekulasi pembelian aset Sritex oleh BUMN menggunakan suntikan dana dari Danantara—sovereign wealth fund (SWF) yang ditargetkan akan mengelola aset senilai Rp14.648 triliun itu.
Kalau benar, skema ini memantik pertanyaan. Sebesar apa dampak tutupnya sebuah korporasi swasta—bukan BUMN atau badan usaha pelat merah—di-bailout dengan uang negara? Tetapi, itu bukan satu-satunya pertanyaan.
Pertanyaan besarnya adalah mengapa baru sekarang pemerintah sibuk menyelamatkan sebuah perusahaan tekstil yang sudah kalang kabut sejak tahun lalu? Sritex bukan satu-satunya korporasi tekstil dalam negeri yang menghadapi krisis selama beberapa tahun terakhir. Selain Sritex, puluhan perusahaan tekstil lain juga terbenam di jurang krisis: ada yang tutup, berhenti berproduksi, atau mengurangi jumlah karyawan (Bisnis.com, 31 Desember 2024).
Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) menyebut hingga akhir 2024 sekitar 60 perusahaan tekstil dan pakaian jadi berhenti beroperasi. Akibatnya, 250.0000 karyawan mengalami PHK. Sritex adalah satu dari 60 perusahaan itu.
Sejak tahun lalu, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian atau Kementerian Perdagangan kerap berdalih krisis tersebut bisa jadi karena persoalan rendahnya daya saing. Jika itu benar, semestinya negara turun tangan sejak lama.
Alih-alih melakukan langkah protektif, tahun lalu pemerintah justru menerbitkan regulasi baru yang menambah beban industri tekstil dalam negeri. Aturan itu adalah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8/2024 yang merevisi Permendag Nomor 36 Tahun 2023. Permendag yang berlaku sejak 10 Maret 2024 itu merelaksasi izin impor dengan alasan mengatasi penumpukan kontainer di pelabuhan.
Permendag No. 8/2024 dianggap sebagai biang keladi tumbangnya industri tekstil dan pakaian jadi dalam negeri. Melalui aturan itu, importir tidak lagi memerlukan pertimbangan teknis (pertek) untuk mendapatkan perizinan impor (PI).
Padahal dalam aturan sebelumnya (Permendag Nomor 36 Tahun 2023), pertek menjadi elemen penting untuk memastikan keberlangsungan industri tekstil dan produk tekstil dalam negeri. Pendek kata, pertek tersebut menjadi garis pertahanan pasar domestik dari serbuan produk impor.
Wajar jika pengusaha tekstil meradang. Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menilai ketiadaan pertek untuk pakaian jadi dalam Permendag No. 8/2024 memicu meningkatnya impor produk tekstil jadi ke pasar dalam negeri. Komisaris Utama PT Sritex Iwan Setiawan Lukminto pada 28 Oktober 2024 juga menyebut permendag tersebut adalah masalah di balik keterpurukan industri tekstil dalam negeri.
Akar Masalah
Kritik yang bermunculan terhadap regulasi itu tak segera direspons pemerintah. Hingga kini permendag itu tidak kunjung direvisi meski kabarnya sedang dalam pembahasan. Entah sampai kapan.
Ini bukan kali pertama pemerintah mengabaikan kritik. Sikap serupa meski tak sama juga muncul saat publik menolak pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja menjadi UU pada 5 Oktober 2020. Salah satu alasan penolakan publik terhadap UU itu adalah terpeliharanya upah minimum rendah dan rentannya karyawan terkena PHK.
UU Cipta Kerja melanggengkan rezim upah murah dengan alasan produktivitas pekerja Indonesia yang lebih rendah daripada negara lain. Padahal, ada skenario ilmiah yang menunjukkan kenaikan upah minimum yang lebih tinggi bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih besar.
Pemodelan yang dilakukan oleh Center of Economic and Law Studies (Celios) menunjukkan ada kenaikan pendapatan domestik bruto (PDB) hingga Rp122,2 triliun jika upah minimum 2025 naik 10% atau lebih tinggi dari formulasi Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. Ini logis karena kenaikan pendapatan bisa mengurangi kemiskinan dan menaikkan daya beli. Kondisi itu berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi.
Tetapi, semua kritik diabaikan. Dalam waktu singkat, atas nama upaya meningkatkan investasi sebesar-besarnya, RUU itu meluncur mulus sebagai UU. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 pada 25 November 2021 yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat juga tak mampu membendung.
Pemerintah berkelit. Terbitlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) yang kemudian disahkan menjadi UU Cipta Kerja jilid II. Semua berjalan mulus tanpa penghalang.
Kini, peringatan dan kritik itu pelan-pelan terbukti. Ekonomi Indonesia tumbuh tak jauh dari angka 5% per tahun sejak 2022. Ini jauh di bawah target pemerintah yang menginginkan ekonomi tumbuh 8% pada 2028-2029. Dengan pertumbuhan ekonomi yang stagnan, penciptaan lapangan kerja juga stagnan.
Badai yang melanda industri tekstil domestik adalah muara dari stagnasi itu. Ketika pertumbuhan ekonomi stagnan, daya beli tak kunjung menguat dan pasar domestik juga lesu darah. Dampaknya, produk-produk tekstil dan pakaian tak terserap oleh pasar domestik yang sudah jenuh.
Di tengah kejenuhan itu, Permendag No. 8/2024 menjadi angin bagi produsen tekstil negara lain membuang produk mereka ke pasar domestik. Ibarat jatuh tertimpa tangga, industri tekstil lokal menghadapi masalah ganda. Pangkalnya sama, yakni kebijakan yang secara epistemologis bermasalah.
Epistemologi menguji “kelayakan” tindakan manusia, termasuk sebuah kebijakan. Dalam dunia akademis, kelayakan itu diuji dengan metode ilmiah. Merujuk rasionalisme Rene Descartes, metode ilmiah berbasis pada pengalaman atau sesuatu yang bisa dibuktikan secara empiris, termasuk sebab-akibat.
Dalam mengambil tindakan yang berdampak pada khalayak luas, pengambil kebijakan semestinya berpikir dengan jalan itu. Semua masalah harus diselidiki penyebab dan dampaknya jika hendak menemukan solusinya. Yang terjadi kini sebaliknya. Keputusan, kebijakan, atau regulasi sering diambil melalui jalan yang tidak semestinya alih-alih ilmiah.
Kembali ke soal Sritex, masalah sebenarnya jauh lebih dalam daripada sebuah pabrik yang pailit. Yang terjadi di Sritex hanya salah satu puncak gunung es masalah yang berpangkal dari regulasi yang tidak masuk akal. Ribuan karyawan di pabrik-pabrik lain—yang telah atau terancam kehilangan pekerjaan karena kondisi serupa—juga tak jelas masa depannya.
Penyelamatan satu entitas usaha tidak cukup tanpa menyelesaikan akar masalahnya. Tanggung jawab negara bukan hanya menyelamatkan satu korporasi swasta, melainkan membuat regulasi yang sehat dan masuk akal bagi seluruh warga.
Revisi Permendag No. 8/2024 bisa jadi belum cukup menjadi obat. Jika demikian, saatnya merevisi UU Cipta Kerja.
Sentimen: neutral (0%)